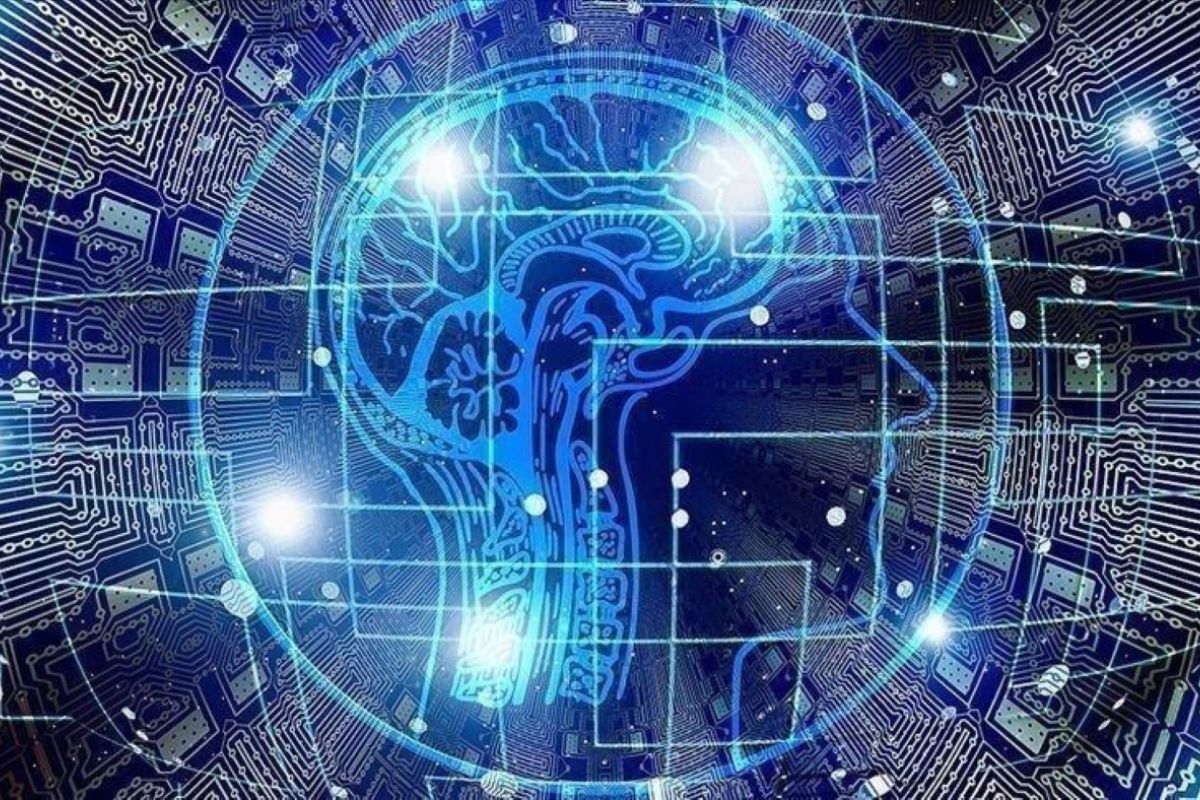Surabaya (ANTARA) - Di era keberlimpahan dan banjir informasi, kita hidup dalam paradoks dan ironi: informasi tidak pernah bisa diakses semudah ini, tetapi akurasi dan kebenarannya justru semakin sulit diverifikasi. Setiap detik ribuan byte informasi baru mengalir di layar gawai. Namun kehadirannya mendatangkan kelelahan kognitif dan kebingungan. Bahkan pada titik tertentu, ia memojokkan kita untuk menghindari berita dan informasi, fenomena yang dikenal sebagai news avoidance.
Maka tantangan terbesar bukan lagi mengakses informasi dan pengetahuan, melainkan memilih, memilah dan menyaring informasi yang benar dan dapat dipercaya. Dulu informasi adalah barang langka yang diperebutkan, di masa ketika kehadiran koran dirindukan setiap pagi. Kini kita menghadapi sebuah era dimana informasi melimpah ruah. Dalam beberapa aspek, PHK di industri media adalah cermin dari fenomena ini, ketika informasi bukan lagi “komoditas” yang berharga karena keberlimpahannya.
Keberlimpahan informasi menciptakan kondisi di mana rentang perhatian dan daya kurasi masyarakat menjadi langka – sebagaimana diingatkan Herbert Simon (1971). Akibatnya, masyarakat sering mengandalkan heuristik kognitif (jalan pintas kognitif) untuk menilai kredibilitas sebuah informasi. Dengan kata lain, kepercayaan akan kualitas informasi kerap ditentukan oleh penampilan atau penyajian informasi tersebut daripada kebenaran isinya. Penelitian terbaru Sinan Aral, penulis Hype Machine, bersama Li, Human Trust in AI Search, menunjukkan kerentanan kognitif ini. Meskipun secara umum kepercayaan terhadap hasil pencarian AI masih rendah, tetapi ketika penyampaiannya dilakukan dengan redaksi yang kuat dan disertai referensi atau sitasi, bahkan ketika referensinya palsu, tingkat kepercayaan penggunanya langsung meningkat signifikan. (Li & Aral, 2025)
Gelombang disrupsi ini tidak mereda. Bahkan makin menjadi ketika AI generatif hadir sebagai aktor baru yang turut menjadi produsen dan penghasil informasi. Struktur otoritas epistemik menjadi bergeser. Fenomena di platform X, dimana pengguna “mengajak” Grok untuk turut berkomunikasi, bisa jadi adalah bentuk pergeseran epistemik semacam ini. Walhasil, pilihan dan perilaku masyarakat dalam menggunakan AI menjadi sangat menentukan. Laporan terbaru UNDP, Human Development Report 2024/2025: A Matter of Choice, menyebut bahwa AI generatif ini adalah teknologi umum (general purpose technology) yang dampaknya sangat ditentukan oleh “pilihan sosial” penggunanya -bukan oleh teknologi itu sendiri. Sehingga pertanyaan yang relevan bukan lagi apakah AI akan menggantikan manusia, tetapi bagaimana kita hidup dan berpikir bersama AI.
Laporan UNDP yang sama juga menyebut bahwa dua pertiga populasi global memperkirakan AI akan mempengaruhi pendidikan, kesehatan dan pekerjaan mereka dalam waktu dekat. Namun ketimpangan dalam representasi budaya dan bahasa dalam sistem AI masih cukup besar. Salah satu contohnya adalah kecenderungan ChatGPT menginternalisasi bias Barat dan kurang merefleksikan nilai-nilai dari negara-negara yang berpendapatan rendah. Hal ini akan memperparah ketimpangan epistemik, ketika sebagian suara menjadi dominan hanya karena sistem di belakangnya mampu menyajikan dalam sebuah penyampaian yang seolah netral.
AI sebagai Aktor dan Kolaborator Baru
Menariknya, peran AI saat ini tak berhenti sebagai penyedia informasi; ia juga menjadi kolaborator dalam produksi konten. Eksperimen lain Aral bersama Ju (2025) menemukan tim yang dibantu AI terbukti jauh lebih produktif daripada tim manusia saja – output per pekerja naik sekitar 60% disertai kualitas teks yang lebih tinggi. (Collaborating with AI Agents: Field Experiments on Teamwork, Productivity and Performance, 2025). AI mengambil alih tugas rutin, sehingga manusia dapat fokus pada kreativitas. Artinya, satu orang bermodal AI kini bisa menghasilkan jumlah konten sebanyak tim konvensional, dengan gaya penulisan yang sama meyakinkan. Dampaknya, batas antara AI sebagai alat bantu dan sebagai kolaborator epistemik makin kabur. AI tak lagi sekadar alat, melainkan mitra atau kolaborator yang turut menyumbang dan memperkaya ide dan narasi. Bahkan personalisasi karakter agen AI dengan karakter pribadi manusia tandemnya juga sangat berpengaruh kepada hasil dari kolaborasi ini dengan sangat signifikan.
Namun efisiensi ini datang dengan harga yang harus dibayar: berkurangnya komunikasi sosial, melemahnya intuisi visual dan pentingnya keselarasan karakter antara manusia dengan AI. Mungkin dalam kerangka inilah, laporan UNDP menekankan pentingnya membangun ekonomi komplementer dimana manusia dan AI saling melengkapi sebagai fasilitator dalam proses. Dalam konteks ini, AI menjadi mitra dalam membungkus gagasan, bukan sekadar mesin yang memuntahkan informasi.
Ketimpangan Komunikasi Otoritatif
Dinamika ini tercermin dalam komunikasi publik di Indonesia. Sering kali informasi keliru lebih dipercaya karena tampilannya meyakinkan, sedangkan pesan resmi pemerintah tidak efektif membangun kepercayaan akibat penyampaiannya lemah, baik dari struktur informasi maupun penyajiannya. Perilaku pengguna di platform X yang mengajak Grok untuk menilai atau memverifikasi informasi dari otoritas adalah salah satu bentuk bagaimana pemanfaatan AI dalam mengungkap ketimpangan komunikasi dari pihak otoritas.
Apabila desain AI yang akan digunakan dalam berkolaborasi menyusun informasi berpihak pada nilai-nilai inklusi, transparansi dan akurasi -bukan tidak mungkin informasi yang disampaikan akan lebih baik untuk mengkompensasi buruknya kualitas komunikasi publik sistem pemerintah kita belakangan ini.
Menuju Ketahanan Epistemik
Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun ketahanan epistemik di era AI ini? Apa yang perlu dilakukan? Pertama, menerapkan desain AI yang bertanggung jawab. Pengembang sistem harus mencegah AI memberi kesan kredibel yang menyesatkan – misalnya, hanya menampilkan referensi yang terverifikasi dan dan transparan mengenai tingkat kepastian jawabannya (Li & Aral, 2025). Kedua, meningkatkan literasi kolaboratif. Masyarakat dan institusi perlu terampil berkolaborasi dengan AI secara kritis. Dan pengguna awam harus belajar memeriksa ulang informasi dari AI dan memahami biasnya. (Ju & Aral, 2025).
Masa depan kita tidak ditentukan oleh AI, hanya jika pilihan sosial kita tepat dalam memanfaatkannya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam laporan UNDP, masa depan AI adalah masalah kebijakan, tata kelola dan pilihan sosial (UNDP, 2025). Atau meminjam postulat Aral ketika membicarakan media sosial, ada 4 faktor yang sangat menentukan: uang/modal, norma sosial, regulasi dan kode/algoritma yang menyusunnya (The Hype Machine, 2020). Postulat ini sepertinya juga berlaku untuk pengembangan AI. Dan sebagai pengguna, kita bisa memilih untuk membiarkan AI mengambil-alih fungsi kognitif kita, atau menjadikannya sebagai kolaborator epistemik untuk memperkuat kapasitas manusia dalam berpikir, memahami dan menghasilkan informasi.----
*)Penulis merupakan Analis di LPPM Stikosa-AWS, serta Relawan di SymbolicID