Menilik sejarah pers Indonesia, agaknya tidak bisa lepas dari peranan sosok Minke dalam penggambaran Pramoedya Ananta Toer dalam buku tetralogi-nya "Bumi Manusia". Minke yang tidak lain dikenal dengan nama Tirto Adhi Soerjo tersebut ternyata adalah sosok yang telah memberikan semua hidupnya untuk meneguhkan fungsi pers melawan kolonialisme Belanda saat itu. Tirto menerbitkan surat kabar "Medan Prijaji" (Medan Priyayi) untuk pertama kalinya di Bandung pada 1 Januari 1907. Melalui "Medan Prijaji" itulah, Tirto mengenalkan bentuk pergerakan modern melawan kolonialisme melalui media cetak. Dari situlah pengungkapan protes tentang kemerdekaan, keadilan, pendidikan politik, dan ideologi mulai disuarakan. Lahirnya "Medan Prijaji" menjadi pendorong peranannya ke sentral pergerakan awal menuju Indonesia merdeka. Salah satu yang pertama kali dilakukan Tirto adalah merusak logika kolonial berkaitan dengan konsepsi "inlander" (merujuk pada orang-orang timur atau bangsa Asia yang menjadi warga kelas dua yakni keturunan Arab, India, dan Tionghoa, sedangkan kelas tiga yakni warga pribumi). Dan, warga Belanda bukanlah termasuk "inlander", melainkan warga kelas pertama atau "vreemde westerlingen" (Barat Asing). Menurut penulis asal Yogyakarta, Muhidin M. Dahlan, dalam tulisannya "Revolusi yang Lahir dari Cetak" (Majalah Basis edisi 1-2, 2009), menyebutkan Tirto merusak formasi rasialis itu dengan menyerukan tesis dialektika baru "Jang terprentah" (yang terperintah) dan "terprentah" (terperintah). Bilapun Tirto menggunakan istilah pribumi, namun pengertiannya bergeser dari pengertian yang telah distigmakan oleh kolonial sebagai "inlander". Tirto menyebutkan bahwa pribumi adalah "sekalian bangsa terprentah" yang meliputi raja-raja, bangsawan, kaum terpelajar, priyayi hingga saudagar. Atas usahanya, Tirto dianggap manusia berbahaya oleh pemerintahan kolonial Belanda, sehingga pemerintahan Hindia Belanda menggelar operasi arsivaris yang sistemik pada 7 Desember 1918 yang akhirnya mengakibatkan Tirto meninggal dunia. Namun, tidak ada penghargaan atas jasa-jasa dalam hidupnya yang kalis bersabung maut berakhir sunyi senyap. Sejarah mengabaikannya dan namanya nyaris tercoret dari sejarah pers dan pergerakan kebangsaan. Cuma ada dua potong berita nekrologi yang ditulis muridnya, Marco Kartodikromo yang mengabarkan kepergiannya dimuat di "Sinar Hindia" (12 Desember 1918) dan "Djawi Hisworo" (13 Desember 1918). "Journalist harus berani mati, bekerja berat membanting diri, sebab dia hendak melindungi, guna mencari anak. Dan tentu saja: berani dihukum dan dibuang, karena dia yang mesti menendang, semua barang yang melangmalang". Nasionalisme Pers Kebangsaan adalah sebuah proses panjang dan melelahkan, ihwal perumusan apa yang disebut identitas untuk pemuliaan manusia. Karena itu, kebangsaan kerap disandingkan dengan perjuangan mencipta kondisi tumbuhnya situasi kemanusiaan yang di kemudian hari memadat menjadi semangat baru bernegara, yakni nasionalisme. Sebelum abad 20, skema perjuangan dominan dilakukan lewat cara-cara peperangan dan adu pasukan di medan laga. Namun dalam dasawarsa pertama abad 20, pola perjuangan memasuki titik perubahan yang cukup signifikan. Titik perubahan itu dipicu oleh sebuah kesadaran baru tentang jalan cetak atau jalan pers. Tesis bahwa bangunan kebangsaan kita didirikan dari tradisi pers bisa dilihat dari fakta sejarah bahwa nyaris seluruh tokoh kunci pergerakan kebangsaan dan nasionalisme adalah tokoh pers. Dan, posisi mereka dalam struktur pers umumnya pemimpin redaksi (hoofdredakteur) atau paling rendah adalah redaktur. HOS Tjokroaminoto yang kita kenal sebagai salah satu "guru pergerakan" adalah pemimpin redaksi "Oetoesan Hindia" dan "Sinar Djawa". "Tiga Serangkai" Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr Tjipto Mangoenkoesoemo menukangi "De Express". Semaoen di usianya 18 tahun sudah memimpin "Sinar Djawa" yang kemudian berubah menjadi "Sinar Hindia". Maridjan Kartosoewirjo menjadi reporter dan redaktur iklan di "Fadjar Asia". Adapun Soekarno menjadi pemimpin redaksi "Persatoean Indonesia" dan "Fikiran Ra'jat". Walau tingkat pendidikan mayoritas rakyat masih rendah, para tokoh pergerakan itu sadar bahwa lembar pers bisa dijadikan medium mengampanyekan ide-ide nasionalisme, selain mimbar-mimbar pertemuan. Dengan pers pula pesan dan gagasan memiliki tingkat aksesibilitas dengan cakupan luas, terutama di kancah internasional. Selain itu, ini menjadi masa percobaan bahasa Indonesia memungkinkan dibentuk dan diberi rumah baru. Namun, jauh sebelum itu semua, kehadiran Tirto Adhi Soerjo dengan "Medan Prijaji" adalah permulaan pertama menjadikan pers sebagai alat pergerakan dan menjadi kuda tunggangan pembibitan semangat membuat rumah bagi bahasa dan usaha menyatukan kolektivitas tanah dan air dalam semesta kesadaran berbangsa. "Medan Prijaji" dengan jargon kebangsaan ini kemudian berfungsi sebagai pers, baik tugasnya sebagai jurnalistik yang memberi kabar, sekaligus mengadvokasi publiknya sendiri dari kesewenang-wenangan kekuasaan maupun kemauan untuk membangun perusahaan pers yang mandiri dan otonom. Selain jalan pers dengan mendirikan perusahaan yang menopang jalannya pers, Tirto juga turut memulai pergerakan lewat jalan berorganisasi. Titik tuju dua tradisi yang disatukan itu adalah penyemaian kesadaran berbangsa. Dari tangan Tirto-lah muncul embrio organisasi yang bercorak seperti Boedi Oetomo, yakni ketika pada 1906 atau dua tahun sebelum Boedi Oetomo, ia mendirikan "Sarekat Prijaji". Dan, Sarekat Islam rancangan pertama Tirto pulalah yang melahirkan banyak sekali tokoh pergerakan, baik kiri, tengah, maupun kanan, saat dia mengonsep Sarekat Dagang Islamijah di Bogor dan kemudian dikembangkan Samanhudi di Surakarta. Tirto-lah yang menyatukan tradisi pergerakan dan tradisi pers untuk satu tujuan, yakni kesadaran berbangsa. Tirto menganggap konsepsi kebangsaan itu tidak dibangun berdasarkan atas suku dan agama, tapi gerakan intelektual, kesadaran bahasa, dan keyakinan ber-Tanah Air. Jadi, jika dicari semua gerakan itu, terutama gerakan nasionalis dan gerakan Islam, bersumbu pada sumur yang sama. Hari Pers Indonesia Setelah mengetahui sejarah awal pers di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa pers bukan sekedar lampiran dari sejarah Indonesia. Ia ada di pusat pergolakan dengan memberikan kesaksian, mencatat, dan sekaligus menjadi turbin pendorong. Maka, tidak berlebihan jika memberikan penghormatan kepada Tirto Adhi Soerjo sebagai pembuka jalan bagi fungsi pers di Indonesia dengan diperingatinya 7 Desember (meninggalnya Tirto) atau 1 Januari (terbitnya surat kabar pertama "Medan Prijaji") sebagai Hari Pers Indonesia. Sementara itu, jika menilik Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap 9 Februari dinilai kurang bisa mengakomodasi semua wartawan di Indonesia. Hal itu dikarenakan pada 9 Februari merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dalam perkembangannya oleh pemerintahan orde baru kemudian disahkan menjadi HPN. Di sisi lain, organisasi kewartawanan di Indonesia yang resmi ada saat ini jumlahnya puluhan seperti halnya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI), Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI), Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI), Serikat Wartawan Indonesia (SWWI), dan lainnya. Merujuk sejarah pers Indonesia dan banyaknya organisasi kewartawanan saat ini, maka perlu kiranya meluruskan kembali Hari Pers Indonesia sebagai tonggak perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Untuk itu, maka kiranya perlu adanya kesadaran dan kesepakatan bersama di kalangan insan pers untuk mengakui bahwa 7 Desember atau 1 Januari adalah Hari Pers Indonesia. Dalam materi kuliah "Pers Kebangsaan" di Susdape XV LKBN ANTARA pada 12 Maret 2009, Direktur Museum Indonesia Taufik Rahzen mengatakan 7 Desember sekaligus adalah hari ditandai sebagai tonggak Hari Pers Indonesia. Menurut dia, tepat di hari ketika Tirto wafat dimana dalam sepanjang hidupnya sudah meneguhkan tugas dan posisi pers: bagaimana pers mesti berhadapan dengan kekuasaan, bagaimana pers mesti membangun perniagaan untuk bisa bertahan dan hidup sehat, serta bagaimana mestinya keberpihakan pers terhadap masyarakat lemah dalam membangun kritisisme dan sekaligus mendorong keswadayaannya. (*)
Berita Terkait

Trump setujui rencana bangun dua kapal perang terbesar dalam sejarah AS
23 Desember 2025 10:50

88 Tahun ANTARA dan saksi sejarah heroisme di Jatim
12 Desember 2025 19:22

Akuatik Indonesia kirim kontingen SEA Games terbesar sepanjang sejarah
6 Desember 2025 19:49

Program Waras tanamkan nilai sejarah pada siswa dengan gembira
20 November 2025 17:25

Pemerintah susun buku sejarah pahlawan nasional dari masa ke masa
10 November 2025 13:31

SMPM 2 Surabaya gelar upacara Hari Pahlawan di Hotel Majapahit
10 November 2025 09:18

Arsip digital dan tantangan dokumentasi kepahlawanan masa kini
10 November 2025 07:25
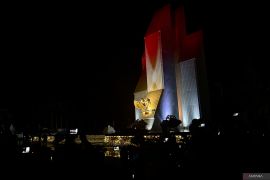
Hari Pahlawan, Prabowo kenang sejarah Pertempuran Surabaya
10 November 2025 06:49


