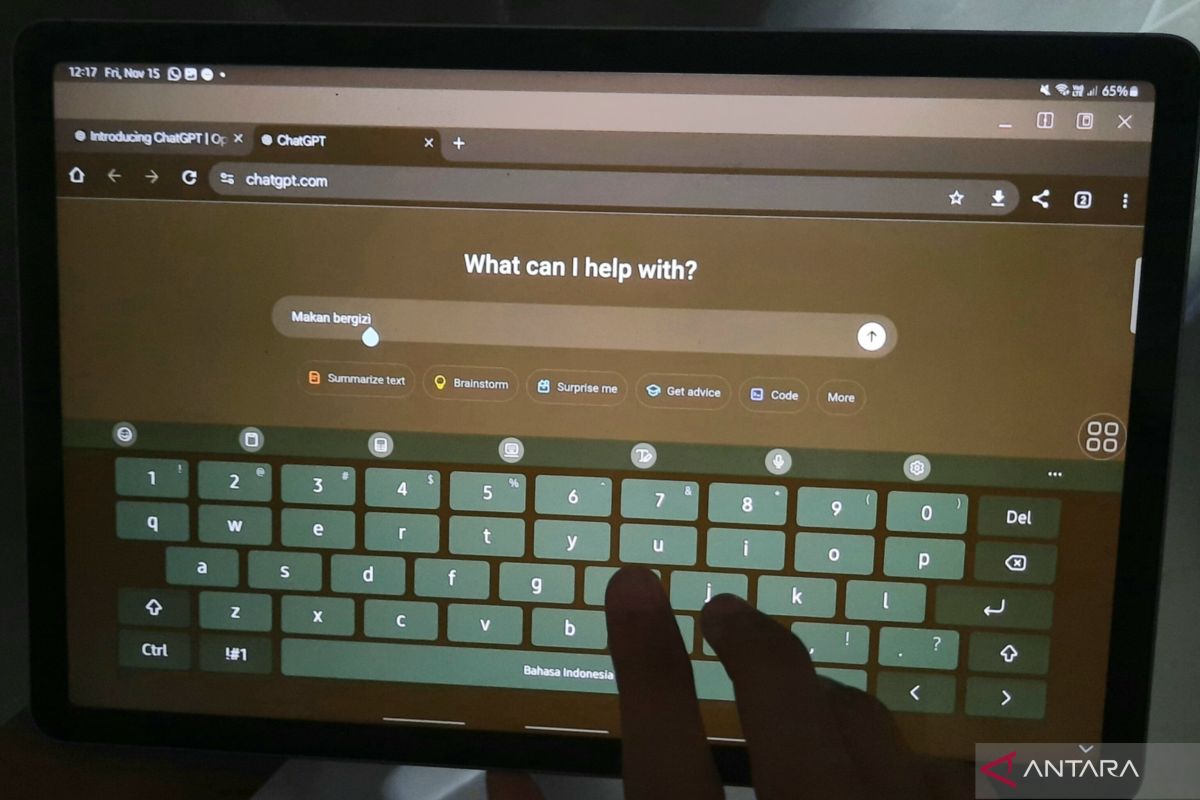Surabaya (ANTARA) - Minggu lalu saya mengetikkan kata kunci “bangunan runtuh al khoziny” di Google untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa tersebut. Yang muncul di bagian paling atas bukan lagi deretan tautan berita, melainkan sebuah ringkasan hasil olahan AI Overview.
Bahasanya kaku tapi efisien, lengkap tapi hambar. Saya membacanya sampai selesai, menutup tab, dan baru menyadari satu hal. Saya belum mengunjungi satu pun situs berita.
Beberapa hari kemudian saya mencoba hal lain. Saya meminta chatbot AI di WhatsApp untuk merangkum artikel panjang tentang kebijakan konstruksi Indonesia. Hasilnya rapi, cepat, dan efisien. Mengenyangkan saya akan asupan informasi yang diperlukan. Tetapi tetap hambar, tanpa rasa.
Kemudian saya teringat seorang penulis senior yang menulis bahwa artikel berita kini terasa seragam, seperti dihasilkan oleh satu mesin yang sama. Kalimatnya rapi, efisien, efektif, dengan struktur yang jelas. Saya setuju. Ada sebuah komentar yang menarik, bahwa hal tersebut memecahkan masalah kecepatan dan kuantitas berita yang dihadapi oleh media. Dan saya kembali mengamininya.
Perubahan Perilaku Pembaca Berita
Perubahan cara kita berhubungan dengan berita berlangsung senyap, tapi cukup radikal. Pertama, tempat kita menemukan berita sudah berubah. Kita tak lagi membuka portal berita atau lembaran koran. Sekarang berita datang sendiri. Lewat beranda, notifikasi, dan sekarang, dalam ringkasan AI.
Editor yang dulu menjadi penjaga gerbang informasi, kini tak lagi punya cukup waktu menangani arus informasi yang melimpah. Kedua, cara kita mengasup informasi pun berubah. Dulu membaca adalah kegiatan pasif untuk memahami. Sekarang mengasup informasi adalah berkomunikasi aktif dengan informasi tersebut.
Teknologi memungkinkan pembaca "menyuruh" untuk meringkas, membuat pointers, hingga menghasilkan informasi baru. Ketiga, ekspetasi terhadap berita ikut berubah. Pembaca ingin serba cepat, personal dan langsung pada pesan. Tapi di saat yang sama, makin segan terhadap apa pun yang tampak terlalu otomatis.
Kombinasi tiga perubahan perilaku ini mengguncang dasar jurnalisme modern. Ia mengubah parameter kebutuhan/demand (apa yang dianggap penting), alur menemukan berita (bagaimana berita didapatkan), dan orisinalitas/otensitas (mengapa sebuah berita perlu dibuat).
Dan ternyata hal ini terjadi secara global.
Minggu lalu Reuters Institute for the Study of Journalism merilis laporan rutinnya untuk tahun 2025. Temuannya cukup mengejutkan, meskipun tidak mengagetkan. Lebih dari separuh responden (61 persen) mengaku menggunakan AI generatif dan sepertiganya menggunakannya setiap minggu.
Penggunaan ini melonjak tajam hanya dalam waktu satu tahun. Namun ada paradoks yang menarik. Hanya 12 persen saja yang merasa nyaman membaca berita yang dibuat oleh mesin. Mayoritas masih lebih percaya pada berita yang ditulis manusia, dengan segala keterbatasan, bias, dan empatinya.
Untuk pertama kalinya, AI generatif yang digunakan untuk pencarian informasi melebihi penggunaan untuk membuat konten. Dalam laporan yang sama, 24 persen penggunaan AI generatif untuk mencari informasi melebihi pembuatan konten teks, gambar maupun video hanya 21 persen. Para penggunanya tidak lagi hanya sekedar "membaca" berita, tetapi "berdialog" dengan berita.
Data lain lebih menarik lagi, dari kelompok pengguna AI untuk berita, 54 persen meminta AI untuk memberi kabar terbaru, 47 persen mengajukan pertanyaan lanjutan tentang suatu isu, dan 40 persen meminta ringkasan berita. 37 persen bahkan memerintahkan AI untuk menilai sumber berita atau membuat berita lebih mudah dipahami (35 persen).
Pendek kata, AI kini bukan hanya alat bantu redaksi, tapi juga asisten redaksi pribadi bagi pembaca berita.
Laporan 2025 ini mengkonfirmasi pertanda yang ditunjukkan oleh temuan riset sebelumnya di 2024 oleh lembaga yang sama. Dalam riset berjudul “OK Computer?”, banyak responden di Inggris, Amerika, dan Meksiko mengaku ambivalen.
Mereka mengakui perlunya efisiensi dengan memanfaatkan AI di belakang layar (untuk menyunting, menerjemahkan, atau memeriksa fakta) namun enggan saat mesin mulai menulis atau menampilkan berita.
Inilah ironi dunia kita saat ini. Kita menikmati pemanfaatan teknologi, namun harus tetap menggenggam nostalgia terhadap integritas jurnalisme.
Sementara itu industri media tampak merasa tenang dan stagnan dengan keyakinan bahwa jurnalisme selalu dibutuhkan. Ada gejala penyangkalan yang meyakini bahwa pembaca akan kembali ke halaman utama berita, asal algoritmanya berpihak pada idealisme jurnalisme.
Ada pula gejala efek plasebo saat media menyatakan diri mengadopsi AI, padahal hanya menambahkan satu plugin dan pelatihan prompting untuk jurnalisnya.
Dan ada optimisme palsu yang meyakini bahwa kepercayaan publik otomatis bertahan hanya karena media tersebut punya sejarah panjang.
Padahal kenyataannya cukup pelik. Kecepatan penyajian berita saat ini bukan lagi keunggulan, tapi ekspektasi minimum. Kepercayaan kepada media juga tidak diwariskan, Ia terus dibangun setiap kali berita dipublikasikan.
Namun harus pula diakui bahwa jurnalisme adalah keniscayaan. Karena di sisi lain, jurnalisme memang masih dibutuhkan, bukan dalam bentuk yang rigid dan dogmatis. Kita masih butuh manusia yang bisa menimbang makna di balik data, memberi konteks ketika dunia hanya menampilkan fragmen.
AI bisa meniru bahasa, tapi belum bisa memanggul tanggung jawab moral. Dan di inilah jantung jurnalisme. Keniscayaan yang lain adalah jurnalisme harus berani bertanya kepada dirinya sendiri.
Menemukan kompatibilitasnya dengan laju perubahan. Apakah efisiensi yang dituntut benar-benar keharusan untuk bisa survive? Apakah kecepatan bisa dilakukan tanpa kehilangan ketelitian? Apakah data bisa menggantikan “rasa” berita? Jika industri media segan menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, maka kehadiran AI bukanlah sebuah ancaman.
Ia adalah cermin yang memperlihatkan bahwa jurnalisme sedang mengalami efek plasebo. Hidup tapi kehilangan makna. Kehilangan relevansi.
Kembali ke layar gawai saya. AI menampilkan ringkasan berita terbaru dengan akurat, ringkas, efisien, penuh informasi. Namun tak ada "suara" disana. Dingin dan beku. Tak ada suara manusia yang menimbang arti peristiwa.
Jurnalisme sejati bukan hanya tentang menyusun fakta, tapi tentang memberi makna pada fakta itu. Manusia masih membutuhkan makna. Dan karenanya kehadiran jurnalisme bisa jadi lebih dibutuhkan dari sebelumnya.
*)Penulis merupakan Analis di LPPM Stikosa-AWS, serta Relawan di SymbolicID